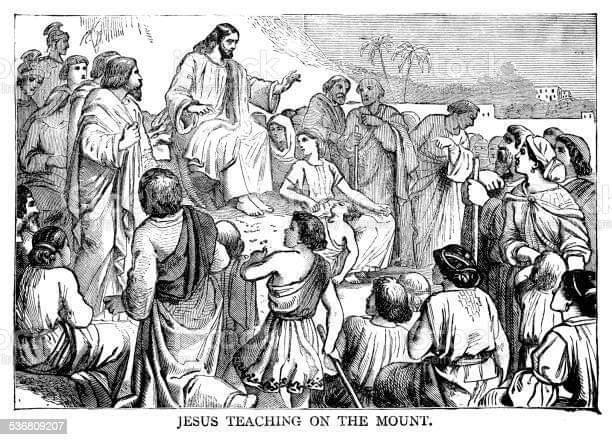“Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Ia ke atas bukit dan setelah Ia duduk, datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya. Maka Yesuspun mulai berbicara dan mengajar mereka,” tulis Matius membuka suatu sesi narasi (Mat. 5-7).
Ya, Yesus “mengajar”. Dia tidak sedang berkampanye seperti seorang “jurkam”, juru kampanye bagi partai atau calon penguasa. Dia juga tidak sedang “melawak” seperti kebanyakan pendeta kini yang satu jam khotbah isinya hanya tentang uang/amplop, seks dan hal remeh-temeh lainnya.
Yesus benar-benar sedang mengajarkan pengetahuan, bukan doktrin (untuk sebuah indoktrinasi loyalitas buta). Dalam bahasa Yunani “mengajar” disebut “didasko”, asal kata yang kemudian kita kenal secara umum sekarang, “didaktik” dan juga “otodidak”. Dalam bahasa Sansekerta disebut “dasra” yang artinya sungguh menginspirasi, “menghasilkan keajaiban”. Pendengarnya memperoleh pengetahuan baru, dan itulah keajaiban sesungguhnya.
Itulah “Khotbah di Atas Bukit” yang menginspirasi banyak orang, mereka para intelektual, budayawan atau sastrawan yang berbeda-beda nama agama hingga kini.
Khotbah Yesus itu mungkin boleh disebut semacam “pidato kebudayaan” yang menyentuh hingga kedalaman kehidupan manusia dalam peradabannya. Suatu pidato yang dekonstruktif, membongkar kepicikan cara berpikir dan laku manusia masa itu, tapi juga masa kini. Yesus berkata dalam satu ucapannya pada uraian yang panjang itu:
“Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga. Berbahagialah orang yang berdukacita , karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai , karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga. Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.”
Yesus benar-benar memutar logika kekuasaan, kesenangan, kesejahteraan, kemenangan, dan segala apa yang dipikir oleh manusia sebagai tujuan hidupnya secara semu! Suatu konsep baru Yesus tawarkan.
Tapi, ini yang absurd. Orang-orang kekristenan yang mengimani Yesus, justru menurut Mahatma Gandhi seorang Hindu India, tidak menghidupi pengajaran Yesus dalam laku hidupnya. Itu berarti tidak paham esensinya. Ada benarnya. Orang-orang Kristen, gereja, kekristenan di era kontemporer sekarang ini apalagi, tampaknya sekadar menjadikan pengajaran Yesus itu sebagai “kata-kata langit” yang rohani saja sehingga lebih gampang menganggapnya itu sebagai bahasa surgawi yang tidak relevan dengan dunia yang fana. Padahal, semua yang Yesus sampaikan itu adalah tentang kehidupan di dunia yang mesti selalu berdialog dengan ideal surga. Jadi, intinya khotbah Yesus di atas bukit itu adalah refleksi dari kehidupan di dunia yang kemudian didialogkan secara spiritual dengan pengetahuan “langit”. Toh, semua mesti praktis dan operasional, bukan untuk kebutuhan malaikat-malaikat di surga, melainkan terutama untuk manusia-manusia rapuh di dunia.
Seorang muslim Indonesia, sejarawan cum sastrawan, Kuntowijoyo tampaknya menangkap esensi “pidato kebudayaan” Yesus itu. Ia tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan, namun justru mampu menangkap teologi Yesus tentang kehidupan. Saya sangat yakin, bahwa Kuntowijoyo ketika menulis novelnya terinspirasi dari narasi Khotbah Yesus di Atas Bukit. Pertama-tama judul novelnya itu adalah “Khotbah di Atas Bukit” (terbit tahun 1976), namun karena memang narasi dan dialog-dialog di dalamnya mengungkap banyak hal yang merupakan esensi dari pengajaran Yesus itu.
Kata Humam kepada Barman, dua tokoh dalam novelnya itu:
“Tinggalkan segala milikmu. Apa saja yang menjadi milikmu, sebenarnya memilikimu. Dan engkau tidak lagi merdeka. Engkau mengira itu kekuasaan, tidak. Itu membuatmu takluk. Membelenggumu!”
Humam, mungkin maksudnya “human” atau manusia, dan Barman atau ‘Brahman” (ilah dalam Hindu), suatu cara kreatif Kuntowijoyo menyampaikan secara simbolik dialog mengenai hakikat kehadiran agama bagi dunia.
Kuntowijoyo benar-benar menemukan esensi dari narasi Yesus tersebut. Sebuah bahaya laten yang selalu menghantui manusia sepanjang sejarahnya: kekuasaan yang mengekang, membelenggu dan mematikan. Lalu, refleksi terdalam untuk keluar dari itu adalah perjuangan atau gerakan untuk bebas dan merdeka! Inilah esensi dari “pidato kebudayaan” Yesus itu. Tidak hanya tentang rohani, yaitu manusia kalah dengan kekuasaan yang merindukan surga, yang entah itu, melainkan tentang suatu gerakan untuk pembebasan. Untuk suatu pembebasan secara fisik, pertama-tama adalah pemikiran yang merdeka!
“Ruang adalah tempat kita bergerak. Gerak adalah hidup kita,” tulis Kuntowijoyo dalam novelnya itu.
Ia benar-benar menangkap semangat narasi itu. Bukan tentang pesimisme atau fatalisme, melaikan suatu optimism menjalani takdir sebagai manusia dalam kehidupan.
Jadi, Yesus mengajar untuk peradaban. Ia mengajarkan pengetahuan untuk banyak orang di segala tempat dan waktu. Yesus adalah Guru peradaban! Dia mengajar untuk publik. Pengetahuannya menjadi diskursus pengetahuan, mempengaruhi pemikiran para filsuf, ilmuwan, aktivis dalam upaya mentransformasi kehidupan. Lalu, bagaimana dengan gereja itu sendiri?
Mahatma Gandhi sangat terpesona dengan Yesus. Dia mengerti misi Yesus dari pengajaran-Nya itu. Gandhi berkata: “Yang aku tangkap dari pesan Yesus, tercakup dalam Khotbah di Bukit. Jiwa dari Khotbah di Bukit berpacu hampir sama seperti Bhagavadgita untuk menawan hatiku”. (dennipinontoan, 09/05/2022)-bersambung ke KEKRISTENAN DAN INTELEKTUALITAS (2)
(tulisan ini diambil dari laman facebook Denni Pinontoan dan dimuat atas seijinnya)